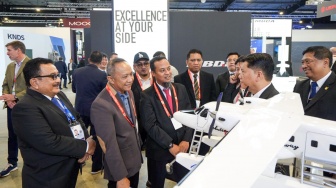- Kawasan ini sejak lama sudah jadi tanah pusaka. Disana juga terdapat kuburan kepala suku.
- Kuburan leluhur mereka baru diakui sebagai situs cagar budaya oleh Bupati Luwu Timur pada Juni 2024
- Lapangan golf sudah terlanjur dibangun. Jasad leluhur pun sebagian tak dikuburkan ulang.
SuaraSulsel.id - Di tepian Danau Matano, Luwu Timur, bentang alam menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Di sanalah pernah berdiri perkampungan tua Karunsi'e, pemukiman pandai besi yang telah ada sejak abad ke-8 Masehi.
Kampung itu tenggelam karena gempa tektonik yang mengubah geologi dasar danau.
Sekretaris Adat To Karunsi'e, Hariyadi Pengke mengatakan, kawasan ini sejak lama sudah jadi tanah pusaka. Disana juga terdapat kuburan kepala suku.
"Itu kuburan kepala suku diobrak-abrik, dijadikan lapangan golf. Padahal makam itu sudah ada sejak 1905," ujarnya usai menghadiri kunjungan kerja Komite II DPD RI di Makassar, Senin, 22 September 2025.
Baca Juga:Aplikasi Ini Bikin Warga Sulsel Lebih Mudah Akses Produk Hukum?
Kuburan leluhur mereka baru diakui sebagai situs cagar budaya oleh Bupati Luwu Timur pada Juni 2024, setelah penelitian mendalam. Namun pengakuan ini datang terlambat.
Lapangan golf sudah terlanjur dibangun. Jasad leluhur pun sebagian tak dikuburkan ulang.
Lebih ironis lagi, lokasi itu dahulu bukan sembarang tanah. Menurut Hariyadi, tempat tersebut pernah menjadi pusat pembelajaran pandai besi bagi orang-orang Belanda pada tahun 1911.
Besi yang ditempa dari Matano bahkan tercatat dalam dokumen digunakan pada masa Gajah Mada dan Hayamwuruk.
"Artefak-artefak itu banyak yang ditemukan di pinggir danau. Dokumentasinya juga tersimpan di museum Leiden," jelasnya.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Bantu Rp1 Miliar Korban Kebakaran di Sorowako
Namun, alih-alih menjadi ruang pelestarian sejarah dan budaya, masyarakat adat Karunsi'e justru terusir.
Saat PT Inco - kini Vale - masuk, warga direlokasi ke Ponada, di kaki gunung. Daerah itu terisolasi, jauh dari lahan pertanian subur.
Mereka dipaksa beradaptasi hanya dengan bercocok tanam sayuran seadanya. "Kami juga tidak pernah menikmati CSR dari PT Vale," kata Hariyadi menegaskan.
Hariyadi mengungkapkan, masyarakat adat Karunsi'e pun menitipkan harapan. Mereka ingin suara mereka tidak lagi terpinggirkan, dan berharap DPD benar-benar menjadikan persoalan ini sebagai atensi serius.
Ancam Pemberhentian
Keluhan masyarakat soal dampak tambang dan pengabaian terhadap situs sejarah mendapat sorotan langsung dari para senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Anggota DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan hampir semua suara yang muncul dalam forum pertemuan itu bermuara pada PT Vale.
"Sehingga, kita di DPD harus berani mengkritik Vale, dan hasilnya akan kita sampaikan langsung ke Menteri ESDM dan Presiden," ujarnya.
Menurut La Nyalla, sudah saatnya DPD bersuara bulat mengawasi operasional perusahaan tambang raksasa itu.
Hal serupa disampaikan Senator Yulianus Henock.
Ia mengingatkan bahwa DPD memiliki Badan Akuntabilitas Publik (BAP) yang siap menampung aduan masyarakat.
Salah satu yang jadi atensi pihaknya saat pipa perusahaan bocor, baru-baru ini.
"Silakan adukan supaya bisa kita usut dan jadikan rekomendasi. Bahkan kita bisa rekomendasikan hentikan operasionalnya karena kontribusinya ke masyarakat sekitar masih minim," tegasnya.
Sementara itu, Senator Graal Taliwao menyoroti masalah keterlibatan masyarakat adat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurutnya, keberadaan masyarakat adat seharusnya dilindungi secara hukum lewat peraturan daerah (Perda).
"Catatan kita, CSR perusahaan wajib melibatkan masyarakat adat. Pertanyaannya, sudah ada Perdanya atau belum? Kepemilikan hutan adat juga sebenarnya sudah diatur dalam peraturan KLH. Jadi harus ada pemetaan dan legalitas. Supaya konflik adat dan korporasi ini bisa diselesaikan," jelasnya.
Bagi Graal, perlindungan hukum menjadi kunci. Jika wilayah adat sudah jelas dan sah secara hukum, perusahaan tambang tidak bisa semena-mena.
"Kalau IUP datang, sementara ada masyarakat adat yang sudah kelola, ya IUP harus menyingkir. Ini yang harus kita dorong di Sulsel dan daerah lainnya," tandasnya.
Kontribusi Sektor Pertambangan Minim
Dari data Direktorat Jenderal Minerba, izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Selatan mencapai 111 izin dengan luas garapan 124.946 hektar, tersebar di 17 kabupaten/kota.
Angka ini menjadikan Sulsel sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan yang cukup padat di Indonesia timur.
Data tersebut terungkap dari kunjungan kerja Komite II DPD RI di Makassar, Senin, 22 September 2025.
Ditjen Minerba mencatat distribusi izin itu bervariasi. Di Barru terdapat 4 izin dengan luas 1.122 hektare, Bone 8 izin dengan 26.394 hektare, Bulukumba 4 izin dengan 155 hektare.
Enrekang 2 izin seluas 1.180 hektare, hingga Luwu Timur yang mendominasi dengan 20 izin seluas 54.767 hektare.
Kabupaten lain juga tak kalah banyak, seperti Pangkep dengan 32 izin, Pinrang 10 izin, serta Sinjai dengan 4 izin yang luasnya mencapai 11.339 hektare.
Komoditas yang digarap pun beragam. Mulai dari besi, emas, galena, mangan, nikel, tembaga, hingga mineral bukan logam.
Dari jumlah tersebut, nikel menjadi primadona dengan 15 izin mencakup 57.512 hektare. Besi mencatat 14.761 hektare, emas 24.336 hektare, dan tembaga 17.614 hektare.
Namun, di balik angka yang terlihat menjanjikan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan di Sulsel menunjukkan tren menurun.
Pada 2024, total PNBP yang masuk hanya Rp462,3 miliar, dengan rincian Rp26,3 miliar dari iuran tetap dan Rp435,9 miliar dari royalti.
Dari jumlah itu, Luwu Timur menyumbang porsi terbesar dengan Rp435,9 miliar royalti. Daerah lain hanya menyumbang angka relatif kecil, bahkan ada yang di bawah Rp1 juta.
Rincian iuran tetap di antaranya, Bantaeng Rp6,1 juta, Barru Rp64 juta, Bone Rp816,4 juta, Bulukumba Rp7,4 juta, Enrekang Rp460 ribu, Gowa Rp13 juta, Jeneponto Rp1,7 juta.
Selayar Rp400 ribu, Luwu Rp978,3 juta, Luwu Timur Rp7,2 miliar, Luwu Utara Rp14 miliar, Maros Rp66,3 juta, Pangkep Rp162,6 juta.
Pinrang Rp51,6 juta, Sidrap Rp16,2 juta, Sinjai Rp2,5 miliar, Soppeng Rp4,8 juta, Takalar Rp40,9 juta, Tana Toraja Rp204,2 juta, Toraja Utara Rp22,6 juta, Wajo Rp3,9 juta, dan Kota Palopo Rp548 ribu.
Di Kabupaten Bantaeng, Wakil Bupati, Sahabuddin mengatakan daerahnya masih sangat bergantung pada dana transfer pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil.
Keberadaan smelter PT Huadi Nickel Alloy sempat menjadi harapan untuk menambah PAD, apalagi industri ini memberi multiplier effect dengan menyerap tenaga kerja lokal.
Sayangnya, dalam beberapa bulan terakhir, operasional Huadi mengalami masalah. Dari lima tungku yang ada, hanya dua yang masih beroperasi.
Tiga lainnya berhenti beroperasi karena pengaruh harga nikel dunia, termasuk aksi demo buruh akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Sekitar 350 pekerja terpaksa diberhentikan. Kami dari pemerintah daerah sudah berusaha melakukan mediasi," kata Sahabuddin.
Keberadaan smelter memang membantu meningkatkan PAD. Namun, Sahabuddin menyebut di sisi lain, dana transfer pusat justru turun hingga 60 persen.
Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya struktur keuangan daerah jika hanya bertumpu pada industri tambang.
Lebih jauh, masyarakat pesisir Bantaeng juga mulai merasakan dampak lingkungan dari limbah smelter perusahaan tersebut.
Nelayan mengeluh hasil tangkapan menurun dan khawatir laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan tercemar.
"Kami harap DPD RI juga memberi perhatian terhadap sisi lingkungan ini. Jangan sampai hanya ekonomi yang dilihat, tapi masyarakat di sekitar justru menderita," ucap Sahabuddin.
Ironisnya, bahan baku yang diolah smelter Bantaeng bukan berasal dari tambang lokal. Nikel justru didatangkan dari Sulawesi Tenggara.
Padahal, data Ditjen Minerba menunjukkan Sulsel punya 15 izin nikel dengan luasan lebih dari 57 ribu hektare.
Fakta ini menjadi pertanyaan, seberapa besar hasil tambang di Sulsel benar-benar kembali untuk kesejahteraan daerah.
Masyarakat di Sulsel juga yang menanggung beban kerusakan alam. Hutan-hutan ditebang, sumber daya alam dikeruk tanpa kendali, dan setiap tahun banjir bandang serta longsor mengancam wilayah tambang.
Namun, keuntungan besar justru tersedot ke pemerintah pusat, sementara dana bagi hasil untuk daerah terus menurun. Pada akhirnya, masyarakat yang menanggung beban dari tambang yang katanya demi kesejahteraan.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing