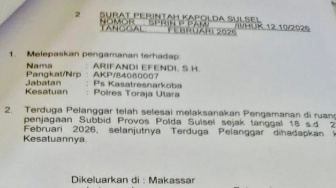SuaraSulsel.id - Suku Ammatoa adalah salah satu suku di Indonesia yang cukup dikenal, walau sangat tertutup. Mereka identik dengan pakaian berwarna hitam, lengkap dengan Passapu' atau pengikat kepala.
Secara administratif, suku Ammatoa terletak di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kajang sendiri terdiri dari dua bagian; Kajang dalam dan Kajang Luar.
Di wilayah Kajang Dalam terdapat Suku Ammatoa. Wilayahnya terdiri dari tujuh dusun dan dihuni kurang lebih 3.000 penduduk.
SuaraSulsel.id sempat menyambangi kawasan adat Ammatoa, Kamis, 23 September 2021. Di pintu masuk kawasan adat ada pendopo, tempat beristrahat bagi pengunjung sebelum memasuki wilayah Ammatoa.
Baca Juga:Akhirnya Warga Desa Adat Amma Toa Kajang Bulukumba Mau Membuat KTP
Di pendopo itu tertulis "Salamakki Antama' Ri Lalang Embaya Rambang Seppanna I Amma". Artinya selamat datang di kawasan tempat kecil Amma.
Jika sudah melewati pendopo tersebut, maka wajib hukumnya bagi pengunjung untuk mengikuti hukum adat masyarakat disana. Mereka memang masih tetap berpegang teguh dengan larangan adat.
Salah satu syarat utama masuk di kawasan ini adalah tidak boleh menggunakan alas kaki, tidak membawa telepon genggam, tidak berbicara kotor dan wajib berpakaian hitam. Itu sudah aturan.
Namun, keasrian wilayah suku Ammatoa benar-benar terasa karena tidak tersentuh modernisasi. Apa saja fakta unik dari masyarakat suku Ammatoa yang tak banyak ditahu publik? Ini dia jawabannya.
![Warga Desa Adat Amma Toa, Kajang, Bulukumba antre melakukan perekaman data e-KTP, Jumat 24 September 2021 [SuaraSulsel.id / Lorensia Clara Tambing]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/24/71161-kajang.jpg)
1. Nama Kepala Suku Tidak Boleh Disebut, Dipilih di Hutan Keramat
Baca Juga:Soeharto Pesan 22 Kapal di Bulukumba Untuk Operasi Militer Papua
Setiap suku yang tinggal di Indonesia pasti memiliki kepala adat. Begitu juga dengan masyarakat di suku Ammatoa. Namun bedanya, kepala adat di sini tidak boleh disebutkan namanya.
Hanya boleh dipanggil Ammatoa. Amma' yang berarti bapak, sementara Toa artinya Tua. Begitupun dengan istrinya yang hanya boleh dipanggil Ando' atau mama.
Ammatoa ini dibantu oleh 26 orang Galla. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya menteri. Mereka membidangi setiap urusan adat.
"Tau anre'a nakulle nisabbu arenna," kata salah satu Galla, artinya beliau tidak boleh disebutkan namanya. Saat kami menanyakan siapa nama pemimpin adatnya.
Pengertian Ammatoa bukan berarti karena bapak yang sudah tua umurnya. Tetapi lebih kepada seseorang yang dituakan karena memiliki pengetahuan yang luas, berperilaku baik, jujur dan bijak.
Ammatoa mempunyai masa jabatan seumur hidup dan dipercaya dipilih langsung oleh Turiek Akrakna atau Tuhan Yang Maha Kuasa melalui proses ritual tertentu. Bukan pilihan rakyat ataupun warisan dari orang tua seperti di kerajaan.
Konon katanya mereka dipilih melalui proses ritual di dalam hutan keramat bernama hutan Tombolo menggunakan ayam dan kerbau. Jika ayam tersebut terbang ke salah satu orang, atau orang tersebut dijilat oleh kerbau, maka dialah yang terpilih menjadi Ammatoa sampai ia meninggal dunia.
Ammatoa juga memiliki kelebihan yang berbeda dibanding warga biasa. Tugas utamanya adalah mengatur masyarakat, menentukan masa tanam dan panen, menerapkan hukum adat dan mengobati yang sakit.
Ia juga sangat dihormati dan dianggap seperti seorang presiden orang Kajang. Oleh karenanya, tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan kepala suku, hanya orang orang yang berkepentingan khusus dan mendesak saja yang bisa bertemu dengannya.
![Warga Suku Ammatoa berjalan kaki tanpa memakai sandal di kawasan adat Ammatoa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan [SuaraSulsel.id / Lorensia Clara Tambing]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/26/51740-suku-ammatoa.jpg)
2. Melepas Pakaian dan Tidak Mandi Selama 40 Hari
Cukup mudah mengenali masyarakat suku Ammatoa yang sedang berduka. Mereka hanya menggunakan sarung hitam tanpa baju selama 40 hari.
Selama itu pula mereka tidak boleh mandi, dan mengganti sarung tersebut. Oleh warga setempat disebut Ikkarambi atau melilitkan sarung pada badan dan diikat pada dada jika berada di dalam rumah. Pada saat keluar rumah, mereka akan A’bohong, atau sarung yang dililit hingga kepala seperti orang memakai kudung.
Selain itu, ada tradisi Ma'basing. Tradisi ini dilakukan setiap sepuluh hari setelah kematian hingga hari ke seratus. Basing adalah alat musik khas Suku Kajang.
Bentuknya mirip seruling panjang. Bedanya, bagian ujung bawah lubang basing ditutup dengan tanduk kerbau. Nyanyian pemain basing juga sulit dimengerti. Mereka menggunakan bahasa khas yang berisi nasihat.
Di suku Ammatoa juga ada namanya Guru Patuntung. Orang ini dipercaya dapat berkomunikasi dengan jenazah. Ia akan mengajak jenazah bercerita dan menanyakan kondisinya di alam kubur.
Keunikan lainnya pada tradisi kematian Suku Ammatoa adalah tidak boleh membawa cabe ke dalam rumah. Masyarakat setempat percaya memakan cabe di dalam rumah akan membuat orang yang meninggal kepedisan di alam kubur.
Pihak keluarga juga tidak boleh menyapu lantai. Hanya boleh menggunakan pakaian untuk membersihkan rumah, karena dipercaya akan membuat badan orang yang meninggal itu bengkak. Namun, bagi masyarakat Ammatoa, kematian ialah suatu perjalanan indah dan penuh nasihat.
3. Berpakaian Hitam, Tanpa Alas Kaki
Warga Kajang secara keseluruhan identik dengan warna hitam. Karena warna ini dianggap sebagai warna tua, sesuai dengan tanah tempat mereka tinggal.
Orang Kajang percaya Suku Ammatoa berdiri di tanah yang tua. Itulah nama desanya dinamakan Tana Toa. Dalam kesejarahan, mereka menganggap masyarakat yang ada di Gowa, Bone, bahkan Luwu berasal dari desa tersebut.
Pengguanaan alas kaki hanya berlaku untuk masyarakat di Kajang Dalam. Alasannya karena alas kaki dianggap sebagai modernitas. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip hidup masyarakat yang hidup disana.
Namun, secara filosofi, alas kaki punya makna tersendiri bagi masyarakat Ammatoa. Warna hitam dipercaya memiliki arti kekuatan dan kesamaan derajat di hadapan sang pencipta. Menurut mereka, bersentuhan langsung dengan tanah menjadi pengingat bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah.
4. Uji Kejujuran Dengan Bakar Linggis
Atunnu Panrolli atau bakar linggis adalah salah satu tradisi suku ini. Masyarakat suku Ammatoa melakukan Atunnu Panrolli untuk menguji kejujuran.
Biasanya dilakukan bagi masyarakat yang sedang berselisih dan tidak menemui titik temu. Linggis kemudian dibakar dalam api sampai memerah, lalu dibacai mantra.
Para tetua adat kemudian berkumpul dan memanggil pihak yang berselisih tadi. Mereka akan disuruh memegang linggis tersebut.
Yang berbohong tentu akan ketahuan karena tangannya akan melepuh. Begitupun sebaliknya, jika jujur maka tidak akan kesakitan sama sekali.
![Kain tenun Suku Ammatoa di kawasan adat Ammatoa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan [SuaraSulsel.id / Lorensia Clara Tambing]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/26/50357-suku-ammatoa.jpg)
5. Harga Pakaiannya Mahal
Kendati tampil sederhana, fesyen masyarakat di suku Ammatoa ternyata harganya sangat mahal. Sarung tenun yang digunakan masyarakat sehari-hari disana dijual dengan harga fantastis. Harganya bisa sampai Rp1,2 juta setiap lembarnya.
Kami sempat menemui salah satu masyarakat yang sedang menenun, Juma. Alasan harganya mahal ternyata karena proses produksinya masih dilakukan secara tradisional.
Satu sarung tenun saja, proses pengerjaannya, kata Juma, bisa sampai satu bulan. Pewarnanya juga tidak menggunakan bahan kimia, tapi pewarna alami dari pohon bernama Taru yang ditanam masyarakat sekitar.
Tenun jadi sumber pendapatan masyarakat Ammatoa. Semua perempuan juga diwajibkan pintar menenun. Selain lihai memasak, mereka harus bisa menenun terlebih dahulu sebelum menikah.
Hasil produksi itu kemudian akan dibawa ke kota untuk dijual. Tak hanya sarung tenun, masyarakat sekitar juga bertani dan berkebun. Saat panen, mereka akan berjalan kaki ke luar kawasan untuk menjual hasil buminya. Berjalan kaki tanpa menggunakan sendal atau sepatu.
6. Seluruh Rumah Menghadap ke Barat
Semua rumah di suku ini menghadap ke arah Barat. Secara simbolis, barat dipercaya sebagai tempat nenek moyang mereka berada. Konsep rumahnya juga seragam, rumah panggung dengan topangan tiang berjumlah 16 buah.
Material yang digunakan juga tidak boleh terbuat dari batu bata atau tanah. Membangun rumah dengan material tersebut adalah pantangan bagi mereka.
Masyarakat di Ammatoa menilai, hanya orang mati saja yang diapit oleh batu bata dan tanah. Jadi jika ada masyarakat yang membangun rumah dengan material yang dipantang itu, maka mereka dianggap sudah mati.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing